Alasan Mengapa Kita Percaya Pada Agama
Alasan Mengapa Kita Percaya Pada Agama – Beberapa psikolog telah mencirikan keyakinan dan percaya pada agama sebagai patologis, dengan melihat agama sebagai kekuatan sosial ganas yang mendorong pemikiran irasional dan perilaku ritualistik. Tentu saja, keraguan para psikolog dan keraguan banyak orang lain sepanjang sejarah tidak membatasi pengaruh kuat agama pada manusia. Agama telah bertahan dan berkembang selama lebih dari 100.000 tahun. Hal ini sudah ada di setiap budaya, dengan lebih dari 85 persen populasi dunia memeluk semacam kepercayaan agama.

Para peneliti yang mempelajari psikologi dan ilmu saraf agama untuk membantu menjelaskan mengapa keyakinan semacam itu dapat bertahan lama. Mereka menemukan bahwa agama mungkin, memiliki pengaruh pada kenyataannya. Dimana menjadi ini sebagai produk sampingan dari cara kerja otak kita. Tumbuh dari kecenderungan kognitif untuk mencari keteraturan dari kekacauan, untuk membuat antropomorfisasi lingkungan kita dan untuk percaya bahwa dunia di sekitar kita diciptakan untuk kita gunakan. raja slot
Agama masih dapat bertahan karena mereka menduga hal ini dapat membantu kita membentuk kelompok sosial yang semakin besar, yang diikat oleh kepercayaan yang sama.
Jika kita berada di jalur yang benar dengan ide produk sampingan ini dan temuannya semakin kuat maka sulit untuk membangun kasus bahwa agama adalah patologi,” kata psikolog Justin Barrett, PhD, direktur kognisi, agama dan proyek teologi di Pusat Antropologi dan Pikiran di Universitas Oxford.
Cenderung percaya
Tidak ada satu kecenderungan kognitif yang mendasari semua keyakinan dan kepercayaan pada agama kita, kata Barrett. Ini benar-benar dasar, kognisi ragam taman yang memberikan dorongan untuk keyakinan agama.
Benang merah kognisi tersebut adalah bahwa mereka menuntun kita untuk melihat dunia sebagai tempat dengan desain yang disengaja, dibuat oleh seseorang atau sesuatu. Anak-anak kecil, misalnya, cenderung percaya bahwa bahkan aspek-aspek sepele dari alam dunia diciptakan dengan tujuan. Menurut serangkaian penelitian oleh psikolog Universitas Boston Deborah Keleman, PhD. Jika Anda bertanya kepada anak-anak mengapa sekelompok batu itu runcing, misalnya, mereka mengatakan sesuatu seperti, Ini agar hewan tidak duduk di atasnya dan menghancurkannya. Jika Anda bertanya kepada mereka mengapa ada sungai, mereka mengatakan itu agar kita bisa memancing.
Orang dewasa juga cenderung mencari makna, terutama selama masa ketidakpastian, saran penelitian. Sebuah studi tahun 2008 dalam Science (Vol. 322, No. 5898) oleh Jennifer Whitson, PhD, dan Adam Galinsky, PhD, menemukan bahwa orang lebih cenderung melihat pola dalam tampilan titik-titik secara acak jika para peneliti pertama kali memprioritaskannya untuk merasakan hal itu. Para peserta tidak memiliki kendali. Penemuan ini menunjukkan bahwa orang-orang siap untuk melihat tanda dan pola di dunia sekitar mereka, para peneliti menyimpulkan.
Orang-orang juga memiliki bias untuk mempercayai hal-hal supernatural, kata Barrett. Dalam karyanya, dia menemukan bahwa anak-anak semuda usia 3 tahun secara alami mengaitkan kemampuan supernatural dan keabadian dengan Tuhan. bahkan jika mereka tidak pernah diajari tentang Tuhan, dan mereka menceritakan kisah yang rumit tentang kehidupan mereka sebelum mereka lahir, apa yang Barrett menyebutnya “pra-kehidupan.”
Apa yang kita tunjukkan adalah bahwa peralatan kognitif dasar kita membiaskan kita pada jenis pemikiran tertentu dan mengarah pada pemikiran tentang pra-kehidupan, akhirat, dewa, makhluk tak terlihat. Dimana mereka melakukan sesuatu, menjadi sebuah tema yang umum bagi sebagian besar agama di dunia, Kata Barrett.
Perlengkapan dasar itu mencakup sistem ingatan yang tampaknya sangat pandai mengingat jenis cerita yang ditemukan dalam banyak teks agama. Secara khusus, penelitian menemukan bahwa kita paling mudah mengingat cerita dengan beberapa elemen, tetapi tidak terlalu banyak elemen yang berlawanan dengan intuisi atau “supernatural”. Dalam sebuah penelitian, yang diterbitkan pada tahun 2006 dalam Cognitive Science (Vol. 30, No. 3), Scott Atran, PhD, dan Ara Norenzayan, PhD, menguji daya ingat orang-orang terhadap konsep yang berkisar dari intuitif sapi yang merumput, hingga sedikit berlawanan dengan intuisi katak yang mengutuk. Hal ini sangat berlawanan dengan intuisi, batu bata berbunga yang memekik. Meskipun orang lebih mudah mengingat cerita intuitif satu jam setelah membacanya, seminggu kemudian, mereka lebih cenderung mengingat cerita yang sedikit berlawanan dengan intuisi.
Temuan ini berlaku baik pada mahasiswa Amerika maupun penduduk desa Maya dari Yucatan Meksiko. Dimana mereka menunjukkan bahwa cerita dengan sedikit elemen yang berlawanan dengan intuisi, seperti yang ditemukan dalam banyak cerita religius, lebih mudah diingat dan, mungkin, lebih mudah ditularkan dari orang ke orang. orang, kata Norenzayan, psikolog di University of British Columbia.
Meskipun demikian, sebagian besar peneliti tidak percaya bahwa kecenderungan kognitif yang membuat kita bias terhadap keyakinan beragama berkembang secara khusus untuk berpikir tentang agama. Sebaliknya, mereka kemungkinan besar melayani tujuan adaptif lainnya. Misalnya, karena orang dengan cepat percaya bahwa seseorang atau sesuatu berada di balik pengalaman yang paling tidak berbahaya. Mereka mungkin menganggap suara desiran angin dari daun sebagai pemangsa potensial. Dalam istilah evolusi, kata Atran, mungkin lebih baik bagi kita untuk salah berasumsi bahwa angin adalah singa dari pada mengabaikan gemerisik dan berisiko kematian.
Tetapi kecenderungan ini juga membuat kita percaya pada konsep seperti Tuhan yang ada di mana-mana. Secara keseluruhan, mudah untuk melihat bagaimana kecenderungan kognitif ini memungkinkan pikiran kita untuk menciptakan agama yang dibangun di atas gagasan makhluk supernatural yang mengawasi hidup kita, kata Atran, direktur penelitian di Center National de la Recherche Scientifique di Paris.
Penelitian semacam itu juga mendukung gagasan bahwa pemikiran religius dalam banyak hal merupakan produk sampingan yang tak terhindarkan dari cara kerja pikiran kita. Psikolog Thomas Plante, PhD, berharap pandangan tersebut akan membantu orang melihat diri mereka sebagai “lebih utuh”.
Kami memiliki sejarah panjang dalam mempercayai bahwa hal-hal yang berhubungan dengan roh ada di satu kelompok, dan sains serta teknologi ada di kamp lain,” kata Plante, profesor dan direktur Institut Spiritualitas dan Kesehatan di Universitas Santa Clara dan presiden Div. APA 36 (Psikologi Agama). Jika ada, karya ini menegaskan kembali bahwa kita adalah manusia utuh dengan biologis, psikologis, sosial, budaya dan spiritual yang semuanya terhubung.
Dasar saraf
Penelitian ilmu saraf jgua mendukung gagasan bahwa otak siap untuk dipercaya, kata Jordan Grafman, PhD, direktur bagian ilmu saraf kognitif di National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Kecenderungan ini, katanya menyebar ke seluruh otak dan mungkin muncul dari sirkuit saraf yang dikembangkan untuk kegunaan lain.
Gagasan yang mendapat banyak perhatian beberapa tahun lalu bahwa ada ‘titik Tuhan’ di otak tempat munculnya pikiran dan perasaan religius sebagian besar telah ditolak,” kata Grafman.
Pada tahun 2009, Grafman menerbitkan studi fMRI yang menunjukkan bahwa pemikiran religius mengaktifkan area otak yang terlibat dalam mengartikan emosi dan niat orang lain. Kemampuan inilah yang dikenal sebagai teori pikiran.
Hasil ini menunjukkan bahwa ketika orang berpikir tentang Tuhan, itu mirip dengan memikirkan figur otoritas khusus. Seperti ibu atau ayah seseorang, kata Grafman. Selain itu, kontemplasi tidak terbatas pada pemikiran religius, meskipun tradisi tertentu seperti doa atau meditasi mungkin memerlukan jenis proses berpikir yang selektif. Secara umum, dia percaya, otak menggunakan sirkuit yang sama untuk memikirkan dan mengalami agama seperti halnya untuk memikirkan dan menangani pikiran atau keyakinan lain.
Apa yang mungkin membuat agama berbeda dari pemikiran duniawi tentang orang tua adalah tradisi kontemplatif. Layaknya seperti meditasi dan doa, yang berpotensi mengubah cara otak terhubung di antara praktisi biasa, kata psikolog University of Wisconsin Richard Davidson, PhD. Karyanya menggunakan fMRI dan EEG untuk mengukur aktivitas otak praktisi meditasi Buddhis jangka panjang selama meditasi menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem perhatian yang lebih kuat dan lebih terorganisir dari pada orang yang baru belajar cara bermeditasi. Intinya, meditasi dan mungkin latihan spiritual kontemplatif apa pun dapat meningkatkan perhatian dan mematikan area otak yang berfokus pada diri.
Meditasi adalah rangkaian latihan mental yang mengubah sirkuit di otak yang terlibat dalam pengaturan emosi dan perhatian, katanya.
Bahkan agama tanpa elemen kontemplatif dapat mengubah sirkuit otak tertentu, menurut penelitian oleh psikolog Universitas Toronto Michael Inzlicht, PhD.
Ini adalah bel alarm kortikal kami, respons ‘uh-oh’ yang bersifat prasadar dan emosional, kata Inzlicht. Saat kami membuat kesalahan, itu membangkitkan, menyebabkan sedikit kecemasan.
Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan tahun lalu di Psychological Science (Vol. 20, No. 3), dia mengukur respons “uh-oh” ini pada orang yang melakukan tugas penamaan warna standar Stroop. Meskipun semua dari 28 peserta studi melakukan kesalahan, pemecatan ERN kurang kuat pada orang-orang yang lebih bersemangat religius dan lebih percaya kepada Tuhan. Mereka lebih tenang dan lebih anggun saat berada di bawah tekanan, kata Inzlicht.
Dalam rangkaian studi kedua, yang diterbitkan pada bulan Agustus di Psychological Science (Vol. 21, No. 8), Inzlicht dan rekan-rekannya menguji apakah orang yang lahir dengan respons ERN yang lebih rendah tertarik pada agama atau apakah agama benar-benar menurunkan “uh- oh” respon. Mereka meminta peserta untuk menulis tentang agama atau tentang sesuatu yang membuat mereka bahagia dan menemukan bahwa mereka yang menulis tentang agama memiliki respons ERN yang lebih rendah, yang menunjukkan bahwa agama meredam respons kecemasan ini. Inzlicht percaya bahwa efek agama mungkin berasal dari kemampuannya untuk membuat orang lebih tenang secara keseluruhan dengan “menjelaskan” fenomena yang tidak kita mengerti.
Perbedaan ini terjadi hanya dalam beberapa perseratus detik, tetapi kami mengusulkan bahwa reaksi yang kurang intens seumur hidup dapat membuat seumur hidup menjadi lebih tenang, kata Inzlicht.
Temuan ini bertautan dengan banyak penelitian dan laporan klinis bahwa orang-orang beragama kurang rentan terhadap depresi dan kecemasan, kata Plante. Praktek Kontemplatif dalam tindakan Spiritualitas, Meditasi, dan Kesehatan menjadi Praktik spiritual adaptif yang dapat menjadi penahan kecemasan dan depresi, kata Plante.
Memiliki keyakinan spiritual juga dapat membuat Anda menikmati hidup yang lebih lama dan lebih sehat. Banyak penelitian menemukan bahwa orang-orang yang religius hidup lebih lama, tidak mudah mengalami depresi. Mereka cenderung tidak menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan, dan bahkan lebih sering pergi ke dokter gigi. Penelitian Inzlicht mungkin memberikan penjelasan parsial untuk temuan ini, kata psikolog Universitas Miami Michael McCullough, PhD.
Pro-sosialitas
Agama mungkin memiliki tujuan utama lainnya dimana agama memungkinkan orang untuk hidup dalam masyarakat yang besar dan kooperatif, kata Norenzayan. Faktanya, penggunaan agama sebagai alat sosial mungkin secara besar menjelaskan daya tahannya dan keberadaannya di mana-mana lintas budaya.
Agama adalah salah satu cara besar yang diterapkan masyarakat manusia sebagai solusi untuk mendorong individu yang tidak terkait untuk bersikap baik satu sama lain, kata Norenzayan.
Secara khusus, agama mendorong orang untuk lebih dermawan dengan mempromosikan kepercayaan pada agen supernatural, menurut penelitiannya. Dalam sebuah studi tahun 2007 Norenzayan dan Azim Shariff membuat para peserta prima dengan pikiran tentang Tuhan dengan meminta mereka menguraikan kalimat yang berisi kata-kata seperti ilahi, roh dan Tuhan. Mereka meminta kelompok peserta lain untuk menguraikan kata-kata yang netral secara agama. Para peserta kemudian memutuskan berapa banyak $ 10 yang harus disimpan dan berapa banyak yang akan diberikan kepada orang asing. Para peneliti menemukan bahwa peserta yang prima dengan pemikiran religius memberikan rata-rata $ 2,38 lebih banyak dari pada peserta lain.
Peneliti University of British Columbia Joseph Henrich, PhD, menemukan dukungan lintas budaya untuk temuan ini dalam penelitian yang diterbitkan pada bulan Maret di Science (Vol. 327, No. 5972). Dia menunjukkan bahwa, di 15 masyarakat yang beragam, orang yang berpartisipasi dalam agama dunia lebih adil terhadap orang asing saat bermain permainan ekonomi daripada orang yang tidak religius.
Agama, dalam arti dapat mengalihkan pemantauan sosial ke agen supernatural, kata Norenzayan. Jika Anda percaya pada Tuhan yang mengawasi, bahkan jika tidak ada yang mengawasi Anda, Anda tetap harus pro-sosial karena Tuhan mengawasi Anda.
Gagasan bahwa agama dapat berevolusi untuk memberi manfaat bagi komunitas sosial yang lebih besar juga terkait dengan karya teoretis psikolog Universitas Virginia Jonathan Haidt, PhD, dan mantan mahasiswa pascasarjana Jesse Graham, PhD. Dimana sekarang menjadi asisten profesor di University of Southern California. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada bulan Februari di Personality and Social Psychology Review (Vol. 14, No. 1), mereka menyarankan bahwa agama berkembang bersama dengan moralitas sebagai cara untuk mengikat orang ke dalam komunitas moral yang besar. Graham dan Haidt berpendapat bahwa melalui cerita dan ritual agama telah dibangun di atas lima landasan moral dasar, yaitu angan menyakiti, bermain dengan adil, setia kepada kelompok Anda, menghormati otoritas dan hidup murni.
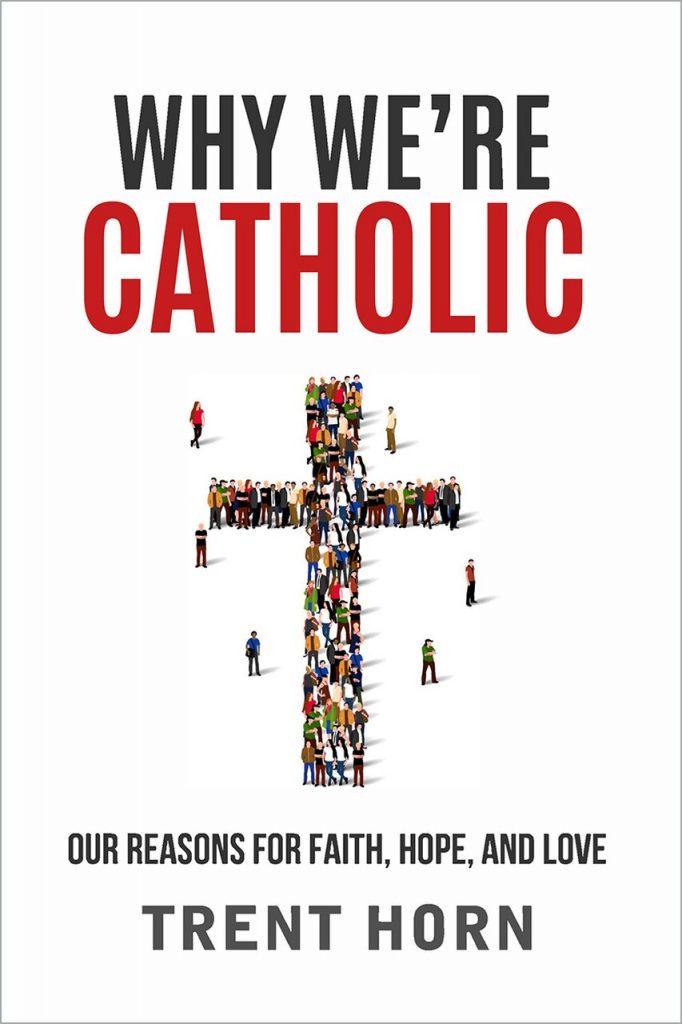
Agama-agama awal menggunakan ritual seperti membatasi makanan tertentu seperti babi dan mengenakan pakaian untuk menunjukkan kesopanan. Selain itu, hal ini juga dapat untuk menunjukkan kepedulian moral ini di depan umum. Ritual tersebut kemudian membantu menyatukan orang dan memungkinkan mereka untuk hidup bersama secara kooperatif, kata Graham.
Tentu saja, sementara agama menyatukan beberapa orang, hal itu terus menyebabkan perpecahan yang dalam, kata Atran, yang telah bekerja sebagai negosiator di beberapa titik panas di seluruh dunia, termasuk Israel. Masalahnya adalah, semakin Anda melihat ke dalam terhadap kelompok agama Anda dan klaim kebajikannya, semakin sedikit Anda dapat melihat ke luar dan semakin tidak percaya Anda pada orang lain, katanya.
Ketidakpercayaan itu menyebabkan banyak perselisihan dan kekerasan di dunia dan merupakan salah satu alasan mengapa ateis baru. Tapi itu akan sulit karena jika agama adalah produk sampingan dari cara kerja otak kita, seperti yang ditunjukkan oleh banyak penelitian baru-baru ini, kata Atran. Apa yang bisa berhasil, kata Norenzayan, adalah mengganti agama dengan komunitas sekuler yang dibangun di atas dasar moral yang sama. Dirinya menyarankan bahwa masyarakat Denmark yang berhasil melakukan ini dengan negara kesejahteraannya yang besar, etika kerja keras nasionalnya dan keterikatannya yang kuat pada kebebasan politik dan individualisme. Tetapi masyarakat seperti itu masih membutuhkan banyak komponen agama, termasuk keyakinan bahwa kita semua adalah bagian dari komunitas moral yang sama.
Untuk mencapainya, peneliti perlu terus dilakukan untuk menyempurnakan pemahaman mereka tentang agama, kata Barrett. Saat penelitian matang dan kami membawa bidang psikologi lainnya, kami pikir kita akan memiliki jendela yang lebih baik ke dalam sifat agama dan ke mana arahnya.
